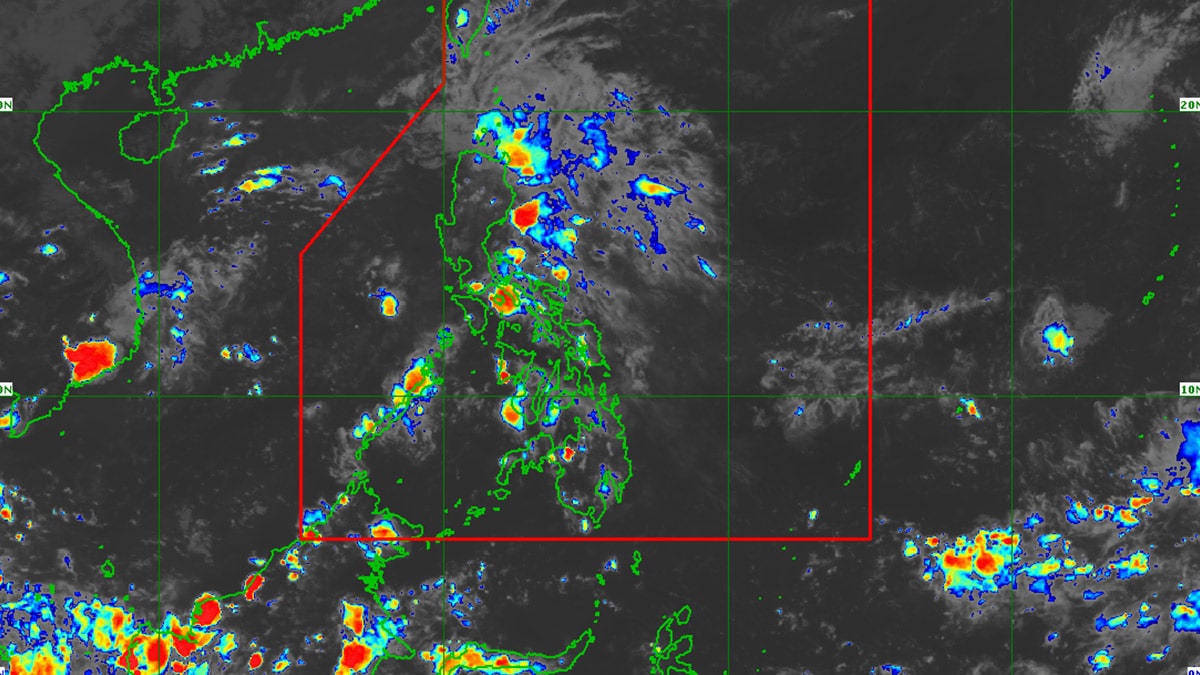Zuha Siddiqui saat ini sedang merancang rumah barunya di Karachi, membuat cetak biru untuk kehidupan masa depannya di kota metropolitan terbesar di Pakistan.
Orang tuanya akan tinggal di lantai dasar rumah ini “karena mereka semakin tua dan tidak mau menaiki tangga,” katanya.
Dia akan tinggal di area terpisah di lantai atas, dengan furnitur yang dia suka. Siddiqui menganggap ini penting karena dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dan menginginkan sebuah tempat yang akhirnya bisa dia sebut sebagai miliknya, katanya kepada Al Jazeera melalui telepon.
Siddiqui menghabiskan lima tahun terakhir bekerja sebagai jurnalis yang menulis topik-topik seperti teknologi, perubahan iklim dan ketenagakerjaan di Asia Selatan. Dia saat ini bekerja jarak jauh sebagai pekerja lepas untuk publikasi lokal dan internasional.
Terlepas dari seluruh rencananya untuk memiliki rumah bagi keluarganya sendiri, Zuha adalah salah satu dari semakin banyak anak muda di Asia Selatan yang masa depannya tidak melibatkan memiliki anak.
Tantangan demografis kini menghadang di Asia Selatan. Seperti di sebagian besar negara lain, angka kelahiran mengalami penurunan.
Meskipun penurunan angka kelahiran terutama terjadi di negara-negara Asia Barat dan Timur Jauh seperti Jepang dan Korea Selatan, negara-negara Asia Selatan yang angka kelahirannya secara umum tetap tinggi akhirnya menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah yang sama.
Secara keseluruhan, tingkat kelahiran 2,1 anak per perempuan diperlukan untuk menggantikan dan mempertahankan populasi saat ini, Ayo Wahlberg, seorang profesor di departemen antropologi Universitas Kopenhagen, mengatakan kepada Al Jazeera.
Menurut publikasi Badan Intelijen Pusat AS pada tahun 2024 yang membandingkan tingkat kesuburan di seluruh dunia, tingkat kelahiran di India sebesar 6,2 pada tahun 1950 telah turun menjadi sedikit di atas 2; diperkirakan akan turun menjadi 1,29 pada tahun 2050 dan hanya 1,04 pada tahun 2100. Tingkat kesuburan Nepal saat ini hanya 1,85; di Bangladesh, 2/07.
Kondisi perekonomian yang memburuk
Angka kelahiran di Pakistan saat ini masih berada di atas angka penggantian sebesar 3,32, namun jelas bahwa generasi mudanya tidak kebal terhadap tekanan kehidupan modern.
“Keputusan saya untuk tidak memiliki anak semata-mata karena alasan finansial,” kata Siddiqui.
Dia mengatakan masa kecil Siddiqui ditandai dengan ketidakpastian finansial. “Saat tumbuh dewasa, orang tua saya tidak benar-benar merencanakan keuangan anak-anak mereka.” Hal serupa terjadi pada beberapa temannya, perempuan berusia tiga puluhan yang juga memutuskan untuk tidak memiliki anak, tambahnya.
Meskipun orang tuanya menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang bagus, biaya untuk mendapatkan gelar sarjana dan magister tidak diperhitungkan, dan tidak lazim bagi orang tua di Pakistan untuk menganggarkan biaya untuk kuliah, katanya.
Meskipun Siddiqui masih lajang, dia mengatakan keputusannya untuk tidak memiliki anak akan tetap berlaku meskipun dia sudah menikah. Dia membuat keputusan tidak lama setelah dia mencapai kemandirian finansial di awal usia 20-an. “Saya rasa generasi kita tidak akan stabil secara finansial seperti generasi orang tua kita,” katanya.
Inflasi yang tinggi, meningkatnya biaya hidup, defisit perdagangan dan utang telah mengganggu stabilitas perekonomian Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 25 September, Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui program pinjaman sebesar $7 miliar untuk negara tersebut.
Seperti banyak anak muda di Pakistan, Siddiqui sangat prihatin dengan masa depan dan apakah dia akan mampu mendapatkan standar hidup yang layak.
Meskipun inflasi telah menurun, biaya hidup di negara Asia Selatan ini terus meningkat, meskipun lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Media lokal memberitakan Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,4 persen di bulan Agustus, setelah naik 2,1 persen di bulan Juli.
(Dis)keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi
Pakistan tidak sendirian. Sebagian besar negara-negara Asia Selatan berjuang dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, meningkatnya inflasi, kekurangan lapangan kerja dan utang luar negeri.
Sementara itu, seiring dengan berlanjutnya krisis biaya hidup global, banyak pasangan yang harus bekerja lebih lama dibandingkan sebelumnya, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk kehidupan pribadi atau komitmen terhadap anak-anak mereka.
Sosiolog Sharmila Rudrappa melakukan penelitian di kalangan pekerja IT di Hyderabad, India, yang diterbitkan pada tahun 2022, dengan topik “infertilitas yang tidak disengaja”. Penelitian ini mengkaji bagaimana seseorang mungkin tidak mengalami infertilitas di awal kehidupannya, namun dapat mengambil keputusan yang, karena keadaan, menyebabkan infertilitas di kemudian hari.
Peserta penelitian mengatakan kepadanya bahwa mereka “kekurangan waktu untuk berolahraga; mereka kekurangan waktu untuk memasak sendiri; dan yang terpenting, mereka kekurangan waktu untuk menjalin hubungan. Pekerjaan tersebut membuat mereka lelah dan kekurangan waktu untuk bersosialisasi dan melakukan keintiman seksual.”
Mehreen*, 33, dari Karachi, sangat memahami hal ini. Dia tinggal bersama suaminya, orang tuanya, dan kakek neneknya yang sudah lanjut usia.
Baik dia maupun suaminya bekerja penuh waktu dan mengatakan mereka “ragu-ragu” untuk memiliki anak. Mereka mengatakan secara emosional mereka sebenarnya ingin punya anak. Secara rasional adalah cerita yang berbeda.
“Saya pikir pekerjaan adalah bagian besar dari kehidupan kita,” Mehreen, yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional, mengatakan kepada Al Jazeera.
Mereka “hampir yakin” tidak akan memiliki anak, dengan alasan biaya sebagai salah satu alasannya. “Sungguh menggelikan betapa mahalnya seluruh bisnis ini,” kata Mehreen.
“Saya merasa generasi sebelum kita melihat hal ini [the cost of raising children] sebagai investasi pada anak. Saya pribadi tidak melihatnya seperti itu,” katanya, menjelaskan bahwa banyak orang dari generasi tua memandang memiliki anak sebagai cara untuk menjamin keamanan finansial di masa depan – anak diharapkan dapat menghidupi orang tua mereka di hari tua. . Dia mengatakan hal itu tidak akan berhasil untuk generasinya – tidak dengan krisis ekonomi yang sedang dialami negara ini.
Lalu ada kesenjangan gender – isu besar lainnya yang membedakan generasi muda dengan orang tua mereka.
Mehreen mengaku sangat menyadari adanya harapan masyarakat bahwa dirinyalah yang akan didahulukan dalam mengasuh anak, bukan suaminya, padahal keduanya adalah pencari nafkah rumah tangga. “Merupakan pemahaman yang wajar bahwa meskipun dia ingin menjadi orang tua yang setara, dia tidak dibesarkan dalam masyarakat ini untuk memahami begitu banyak tentang mengasuh anak.
“Saya dan suami memandang satu sama lain sebagai pasangan yang setara, namun apakah ibu kami memandang kami sebagai pasangan yang setara? Mungkin tidak,” katanya.
Selain uang dan tanggung jawab rumah tangga, faktor lain juga mempengaruhi keputusan Mehreen. “Tentu saja, saya selalu berpikir bahwa dunia akan datang suatu hari nanti. Mengapa membawa kehidupan ke dunia yang kacau ini?” – katanya datar.
Seperti Mehreen, banyak warga Asia Selatan yang khawatir mengenai membesarkan anak-anak di dunia yang ditandai oleh perubahan iklim dan masa depan yang tampaknya tidak menentu.
Mehreen ingat bagaimana, sebagai seorang anak, dia tidak pernah berpikir dua kali untuk makan makanan laut. “Sekarang harus banyak berpikir tentang mikroplastik dan sebagainya. Jika sekarang sangat buruk, bagaimana jadinya dalam 20, 30 tahun ke depan?”
Memperkenalkan anak pada dunia yang rusak
Dalam kumpulan esainya, Apocalypse Babies, penulis dan guru asal Pakistan Sarah Elahi menggambarkan kesulitan menjadi orang tua saat ini, ketika kecemasan terhadap iklim mendominasi kekhawatiran anak-anak dan remaja.
Dia menulis tentang bagaimana perubahan iklim menjadi isu yang disembunyikan sepanjang masa kecilnya di Pakistan. Namun, seiring dengan meningkatnya suhu global, ia menyadari bahwa anak-anak dan murid-muridnya semakin hidup dalam “kecemasan antropogenik”.
Perasaan Elahi benar bagi banyak orang. Dari meningkatnya turbulensi penerbangan hingga gelombang panas dan banjir yang lebih mematikan, dampak buruk dari kerusakan lingkungan dapat membuat kehidupan lebih sulit di tahun-tahun mendatang, kata para ahli dan organisasi termasuk Save the Children.
Siddiqui mengatakan bahwa ketika dia menulis tentang lingkungan hidup sebagai jurnalis di Pakistan, dia menyadari bahwa memiliki anak tidak akan menguntungkan. “Apakah kamu benar-benar ingin membawa seorang anak ke dunia yang bisa menjadi bencana setelah kamu mati?” – dia bertanya.
Beberapa penulis dan peneliti, termasuk mereka yang terkait dengan lembaga think tank AS, Atlantic Council dan University College London (UCL), sepakat bahwa Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang paling terkena dampak perubahan iklim.
Laporan Kualitas Udara Dunia tahun 2023 yang diterbitkan oleh kelompok iklim Swiss IQAir menunjukkan bahwa kota-kota di negara-negara Asia Selatan termasuk Bangladesh, Pakistan, dan India memiliki kualitas udara terburuk dari 134 negara yang dipantau.
Kualitas udara yang buruk mempengaruhi semua aspek kesehatan manusia, menurut ulasan yang diterbitkan oleh Environmental Research Group di Imperial College London pada April 2023.
Tinjauan ini menemukan bahwa ibu hamil, misalnya, menghirup udara yang tercemar sehingga dapat menghambat perkembangan janin. Selain itu, terdapat hubungan antara kualitas udara yang buruk dan berat badan lahir rendah, keguguran, dan bayi lahir mati. Bagi remaja putri seperti Siddiqui dan Mehreen, itu hanyalah alasan lain untuk tidak memiliki anak.
Takut akan isolasi
Siddiqui telah membangun sistem dukungan yang kuat dari teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sama; sahabatnya sejak kelas 9, mantan teman sekamar kuliahnya, dan beberapa orang yang dekat dengannya dalam beberapa tahun terakhir.
Idealnya, katanya, dia akan hidup dalam komunitas bersama teman-temannya.
Namun rasa takut akan sendirian di kemudian hari terkadang masih membekas di benak Siddiqui.
Seminggu sebelum dia berbicara kepada Al Jazeera, dia sedang duduk di sebuah kafe bersama dua temannya – wanita berusia tiga puluhan yang, seperti dia, tidak tertarik untuk memiliki anak.
Mereka berbicara tentang ketakutan mereka akan kematian sendirian. “Itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saya,” kata Siddiqui kepada teman-temannya.
Tapi sekarang dia mengabaikannya, berharap itu hanya ketakutan yang tidak masuk akal.
“Saya tidak ingin memiliki anak hanya untuk memiliki seseorang yang merawat saya ketika saya berusia 95 tahun. Menurutku itu konyol.”
Siddiqui mengatakan dia mendiskusikan percakapan di kedai kopi dengan sahabatnya.
“Dia menjawab, ‘Tidak, kamu tidak akan mati sendirian.’ Saya akan berada di sana.”
*Nama diubah demi anonimitas.