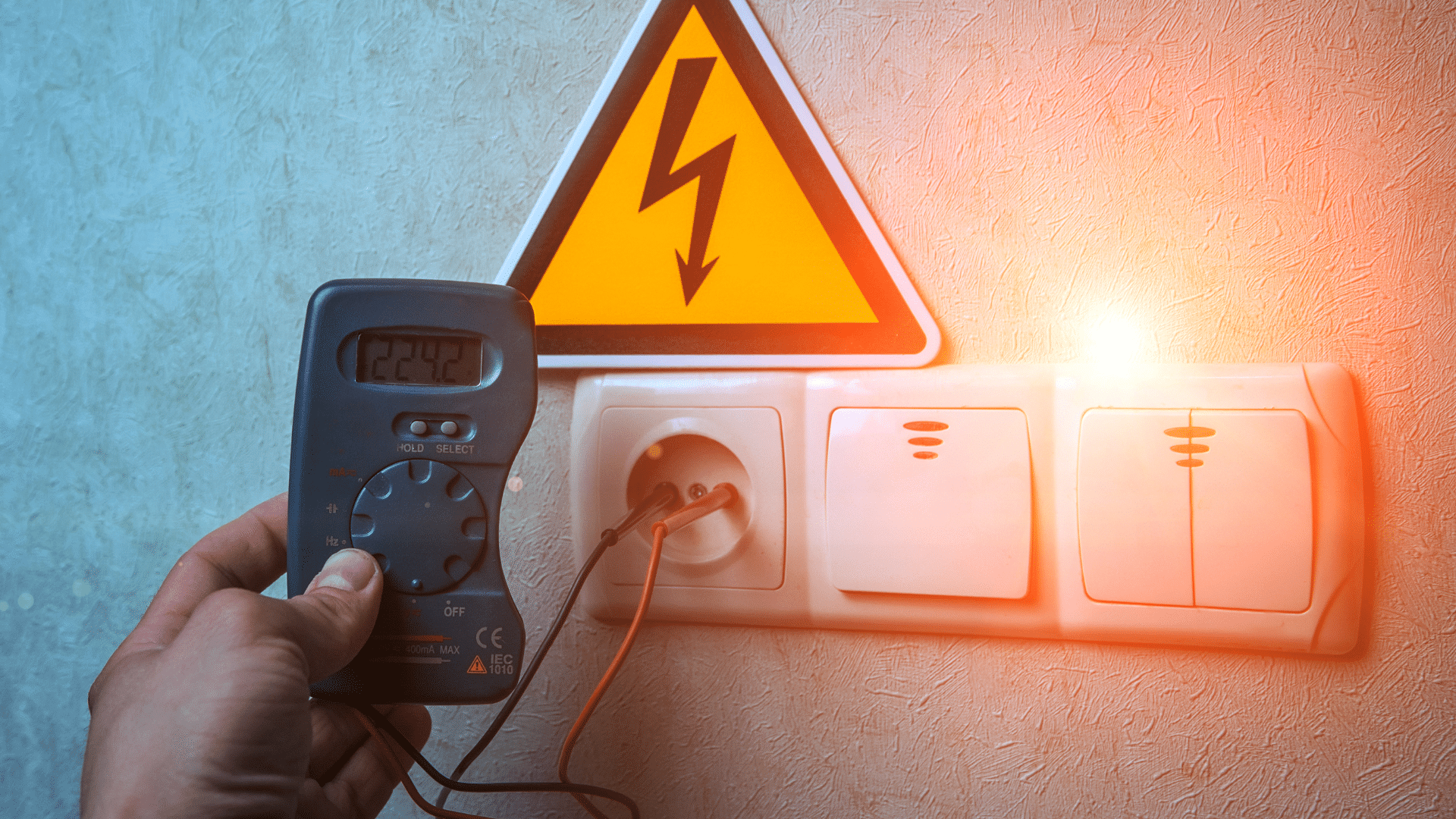Dalam pemilu AS, isu-isu “roti dan mentega” biasanya dikatakan mendorong masyarakat untuk memilih dan menentukan pilihan mereka, dan kekhawatiran mengenai faktor-faktor ekonomi seperti inflasi dan biaya hidup sering kali menjadi prioritas utama para pemilih.
Ada kebijaksanaan yang menyatakan bahwa isu-isu yang lebih jauh seperti kebijakan luar negeri tidak menentukan pemilu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu penasihat pemilu Bill Clinton pada tahun 1992: “Bodoh, ini soal ekonomi.” Pada saat itu, Presiden saat itu George H. W. Bush baru saja mengusir pasukan Irak dari Kuwait, sebuah “kemenangan” kebijakan luar negeri yang tidak menjamin Bush memenangkan pemilu. Pandangan ini telah menjadi pokok dalam siklus pemilu, namun para sejarawan dan analis memperingatkan bahwa pandangan tersebut hanya sebagian saja yang benar.
Mereka memperingatkan bahwa kebijakan luar negeri penting dalam pemilihan presiden AS, terutama yang sangat dekat sehingga dapat diputuskan dengan selisih yang sangat tipis, seperti yang dijanjikan pada pemilu kali ini.
Dalam menghadapi perang yang berkepanjangan di Ukraina dan perang yang meluas di Timur Tengah yang mana Amerika Serikat telah menghabiskan banyak uang dan semakin terlibat, serta isu-isu utama kebijakan luar negeri seperti imigrasi dan perubahan iklim, banyak pemilih yang memprioritaskan , jelas bahwa perekonomian tidak akan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan cara masyarakat Amerika memilih bulan depan.
Meskipun perekonomian tetap berada di peringkat teratas, survei pemilih pada bulan September yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan hal tersebut 62 persen para pemilih menyebut kebijakan luar negeri sebagai isu yang sangat penting bagi mereka. Kekhawatiran terhadap kebijakan luar negeri merupakan hal yang sangat penting di kalangan pemilih Trump – 70 persen di antaranya – namun 54 persen pemilih Harris juga menempatkan kebijakan luar negeri sebagai prioritas utama bagi mereka, begitu pula mereka yang memasukkan nominasi Mahkamah Agung sebagai salah satu prioritas utama mereka.
“Dalam persaingan yang sangat ketat seperti duel tahun ini antara mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris, masalah kebijakan luar negeri dapat menjadi penentu,” tulis Gregory Aftandilian, pakar kebijakan Timur Tengah dan peneliti kebijakan luar negeri AS, dalam sebuah artikel baru-baru ini. kertas. “Khususnya, pandangan para pemilih mengenai bagaimana para kandidat akan menangani perang Israel-Hamas-Hizbullah dan Rusia-Ukraina dapat menjadi penentu bagi negara-negara yang menjadi medan perang dan, oleh karena itu, bagi pemilu.”
Mitos pemilu di AS
Pandangan bahwa kebijakan luar negeri tidak terlalu berpengaruh dalam pemilihan presiden AS baru muncul dalam tiga dekade terakhir. Pada saat itu, jajak pendapat terhadap masyarakat Amerika yang dilakukan sebelum pemilu menunjukkan bahwa 30 hingga 60 persen dari mereka menyatakan kebijakan luar negeri sebagai isu paling penting yang dihadapi negara tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dingin, angka tersebut turun menjadi lima persen.
“Ini adalah ide pasca-Perang Dingin,” Jeffrey A Friedman, seorang profesor pemerintahan di Dartmouth College yang mempelajari pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, mengatakan kepada Al Jazeera.
Bahkan setelah 9/11, Amerika Serikat melancarkan perang bertahun-tahun di Irak dan Afghanistan yang merugikan Amerika 8 triliun dolarSelain kematian ribuan orang, kebijakan luar negeri memainkan peran sekunder dalam pemilu tersebut, meskipun kebijakan tersebut membantu mantan Presiden George W. Bush memenangkan pemilu kembali pada tahun 2004. Meskipun invasi ke Irak pada tahun 2003 kemudian membuatnya sangat tidak populer, Bush saat itu masih menduduki posisi kedua. kemenangannya sebagian karena ia mampu memanfaatkan peran kepemimpinannya setelah serangan 9/11.
Friedman mencatat bahwa di masa lalu, kemampuan seorang kandidat untuk menggambarkan dirinya sebagai orang yang kuat dan tegas di mata dunia lebih penting daripada rincian apa pun mengenai keputusan kebijakan luar negerinya.
Dia mengutip mantan Presiden AS Lyndon Johnson, yang membuka jalan bagi eskalasi AS di Vietnam selama kampanye presiden tahun 1964. Johnson tahu bahwa Amerika tidak menginginkan perang di Vietnam, namun dia juga tahu bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia akan “keras terhadap komunisme,” kata Friedman.
“Para pemilih selalu skeptis terhadap penggunaan kekuatan di luar negeri, namun mereka juga skeptis terhadap para pemimpin yang tampaknya mundur dalam menghadapi agresi asing,” tambahnya. “Calon presiden berusaha meyakinkan pemilih bahwa mereka cukup kuat untuk menjadi panglima. Mereka tidak ingin berjanji untuk melibatkan Amerika Serikat dalam konflik militer, namun mereka juga harus menghindari kesan bahwa mereka akan mundur ketika dihadapkan pada pilihan tersebut.”
Hal itulah yang coba dilakukan oleh Donald Trump dan Kamala Harris ketika Israel memperluas perang yang telah berlangsung selama setahun di Gaza hingga ke Lebanon dan berjanji untuk menyeret seluruh wilayah tersebut, dan mungkin AS, ke dalam konflik lebih lanjut.
Seperti perlawanan terhadap Perang Vietnam, ketika Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 1968 di Chicago menjadi ajang protes massal yang ditindas secara brutal oleh polisi, dukungan AS terhadap Israel terbukti sangat memecah belah di AS, yang berujung pada aksi duduk berskala nasional di kampus-kampus dan Israel. masalah kebijakan luar negeri yang secara rutin diminta untuk didiskusikan oleh para kandidat.
“Harris dan Trump memiliki kaitan yang sangat mirip dengan hal ini,” tambah Friedman. “Jadi mereka mencoba menciptakan kesan samar bahwa mereka bisa menangani konflik dengan kompeten tanpa membuat janji apa pun yang bisa memecah belah.”
Pemungutan suara di Gaza
Membuat janji-janji yang tidak jelas mungkin merupakan sebuah strategi, namun mengingat keterlibatan Amerika Serikat yang mendalam dalam perang Israel di Timur Tengah, yang disubsidi secara besar-besaran oleh Amerika Serikat dan kini berisiko terlibat lebih jauh, hal ini mungkin tidak cukup.
Mengingat jajak pendapat yang tidak tepat dan margin dalam banyak jajak pendapat sangat tipis, sulit untuk memprediksi seberapa besar dampak kekecewaan sebagian orang Amerika terhadap dukungan AS terhadap Israel dan apakah pemilih pro-Palestina akan memilih Trump, memilih pihak ketiga, dan apakah pemilih pro-Palestina akan memilih Trump. tetap di rumah atau dengan enggan memilih untuk melanjutkan kebijakan Harris yang dijanjikan kepada Presiden Joe Biden.
Namun kemungkinan bahwa pemungutan suara protes di Gaza dapat mempengaruhi pemilu bukanlah hal yang mustahil seperti yang ditunjukkan oleh beberapa jajak pendapat.
“Jika Harris kalah, dan dia kalah karena umat Islam tidak memilihnya di negara bagian yang dipilih, maka hal itu terjadi secara langsung karena Gaza,” Dalia Mogahed, peneliti di Institut Kebijakan dan Pemahaman Sosial (ISPU), mengatakan kepada Al Jazeera . “Masalah paling penting yang dikemukakan umat Islam dalam menilai kandidat adalah pendekatan mereka terhadap perang di Gaza.”
Mogahed mengutip ISPU tes yang menunjukkan bahwa 65 persen suara Muslim jatuh ke tangan Biden pada pemilu tahun 2020 – angka yang jauh lebih besar dibandingkan margin yang membuatnya memenangkan negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama. Ketika Biden keluar dari pemilu pada bulan Juli, jumlah pemilih Muslim yang mengatakan mereka akan mendukungnya lagi telah turun menjadi 12 persen.
Harris menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Israel, dan meskipun ia terkadang melunakkan bahasanya dan berbicara tentang penderitaan warga Palestina dengan cara yang lebih berempati, ia menyatakan tidak ada kesediaan untuk mengubah kebijakan dan tidak jelas apakah ia berhasil mendapatkan kembali dukungan yang dimiliki Biden. hilang.
Meskipun studi ISPU berfokus pada Muslim Amerika, jajak pendapat terhadap pemilih Arab menemukan hasil serupa dan sekali lagi mengidentifikasi masalah kebijakan luar negeri – perang Gaza – sebagai faktor kunci dalam pemilu.
Ada preseden sejarah, kata Friedman, mengutip blok pemungutan suara seperti warga Kuba-Amerika di Florida yang menentang normalisasi dengan Kuba atau komunitas Eropa Timur di AS yang mendukung upaya Clinton untuk memperluas NATO pada pertengahan 1990an kandidat lain berdasarkan preferensi kebijakan luar negeri, fenomena seperti Gerakan Nasional Non-Blok adalah hal baru dan menandakan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan luar negeri AS yang melampaui batas partai.
“Gagasan bahwa kelompok demografi tertentu mempunyai preferensi kebijakan luar negeri yang kuat bukanlah hal baru,” kata Friedman. “Saya tidak yakin kita pernah melihat hal ini sebelumnya, ini merupakan ancaman yang cukup jelas dari masyarakat untuk tidak memberikan suara pada kandidat yang biasanya Anda dukung.”
Namun bukan hanya warga Muslim, Arab-Amerika, dan lainnya, termasuk banyak pemilih muda, yang mungkin melihat perang di Gaza sebagai masalah paling mendesak dalam siklus pemilu ini, yang juga menjadi perhatian penting bagi kebijakan luar negeri.
Di masyarakat, terutama kelompok yang paling terpinggirkan, kebijakan luar negeri sering kali dipandang bukan sebagai masalah yang jauh, namun sebagai “masalah internal,” kata Rasha Mubarak, seorang aktivis komunitas di Orlando, Florida, kepada Al Jazeera.
“Pemilih Amerika dapat menilai kondisi material kehidupan sehari-hari mereka dan menghubungkannya dengan apa yang terjadi di Gaza,” kata Mubarak, mengutip kebutuhan sosial, mulai dari layanan kesehatan hingga bantuan badai, yang dipahami masyarakat akan mendapat manfaat dari dana publik. Amerika Serikat berinvestasi untuk mendukung upaya militer di luar negeri.
“[It’s] terlepas dari masalah moral terkait dengan fakta bahwa hampir 200.000 warga Palestina tewas akibat pemboman dan genosida Israel,” kata Mubarak, mengacu pada perkiraan potensi total korban jiwa dalam perang tersebut. “Pemilih Amerika memahami keterhubungan.”